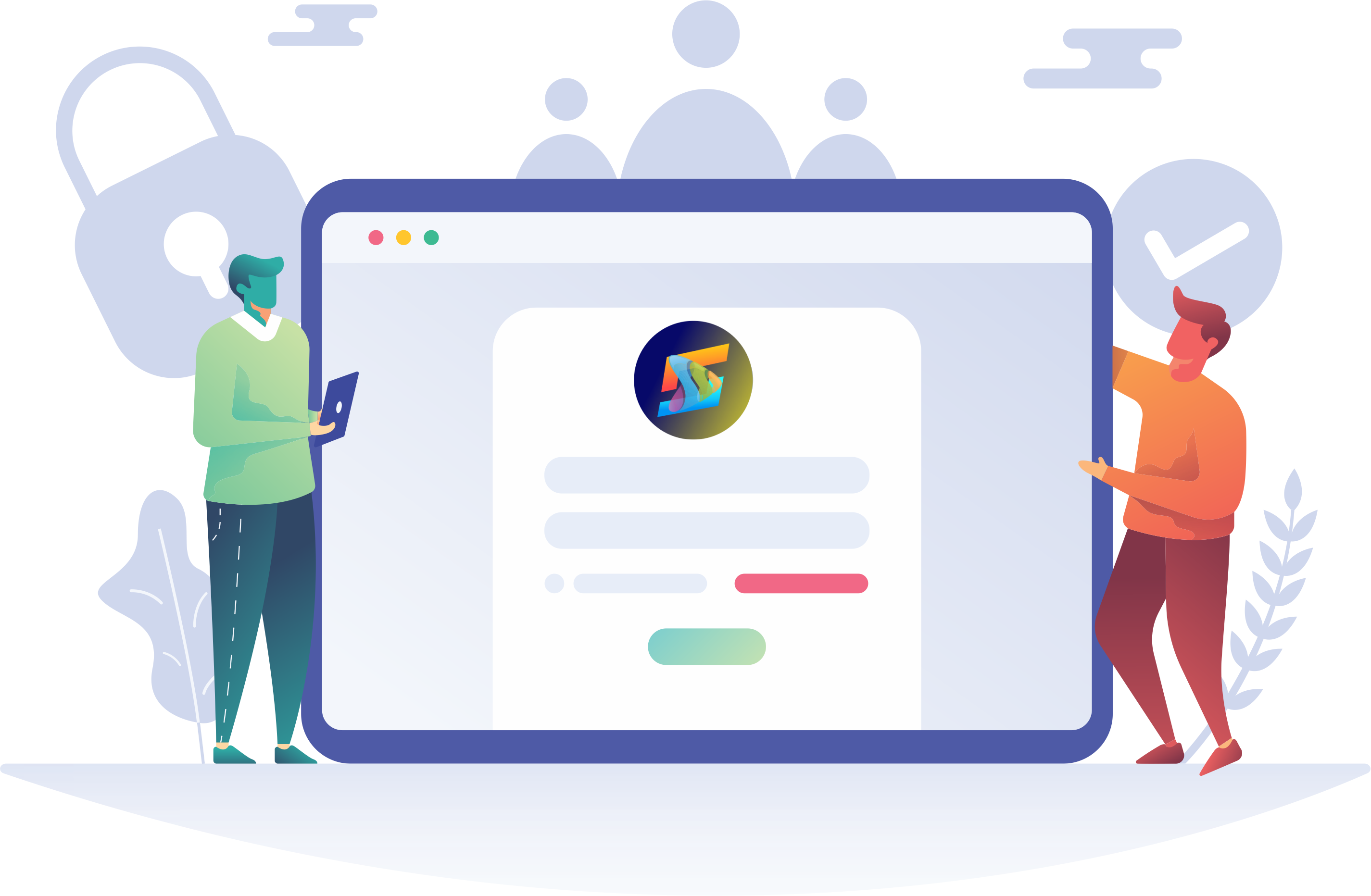Sinopsis.co.id, JEMBER – 4 Agustus 2025.
Dunia tengah menghadapi krisis ekologis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suhu bumi terus meningkat, es di kutub mencair, hutan tropis yang dulu lebat kini berubah menjadi lahan gersang akibat deforestasi, sementara polusi udara dan air meracuni kehidupan makhluk di darat dan laut.
Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2023 memperingatkan bahwa waktu kita untuk bertindak semakin menipis. Di tengah laju perusakan lingkungan ini, muncul pertanyaan yang lebih mendalam, di mana peran agama dan spiritualitas dalam menyikapi krisis ini?
Ekoteologi hadir sebagai respons teologis dan etis terhadap kerusakan ekologis. Ia merupakan persimpangan antara teologi, etika, dan ekologi yang menyoroti hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesamanya. Lebih dari sekadar refleksi keimanan, ekoteologi menuntut aksi nyata: bagaimana nilai-nilai spiritual dapat menjadi fondasi untuk perlindungan lingkungan.
Artikel ini berupaya menggali bagaimana kesadaran spiritual dari berbagai tradisi agama, khususnya Islam, dapat menginspirasi tanggung jawab ekologis. Pertanyaannya kemudian: jika manusia mengaku beriman, mengapa mereka justru menjadi agen utama perusakan bumi? Apakah keimanan kita belum cukup membumi?
Melalui pendekatan yang menggabungkan data ilmiah, refleksi teologis, dan narasi inspiratif, mari kita telusuri kembali makna iman dalam merawat ciptaan-Nya.
*Spiritualitas Ekologis dalam Berbagai Tradisi Agama*
A. Akar Spiritualitas Lingkungan
Sejak awal peradaban, agama telah menjadi pedoman hidup yang membimbing manusia dalam memahami eksistensinya—termasuk relasinya dengan alam. Dalam berbagai tradisi spiritual, ditemukan ajaran mendalam tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.
Dalam tradisi Kristen, konsep stewardship atau penatalayanan menekankan bahwa manusia adalah penjaga ciptaan Tuhan, bukan pemilik mutlak. Dalam Kitab Kejadian (Kejadian 2:15), Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden “untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.” Pesan ini bukan sekadar tugas pertanian, melainkan simbol tanggung jawab etis terhadap alam. Teolog Kristen kontemporer seperti Sallie McFague dan Leonardo Boff memperluas konsep ini dengan menegaskan bahwa Bumi harus diperlakukan sebagai tubuh Kristus yang harus dihormati dan dilindungi.
Dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah dimuka bumi, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah [2]:30: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” Istilah khalifah bermakna pemegang amanah atau wakil Allah, yang harus menjaga keseimbangan ciptaan-Nya. Islam tidak hanya memuat aturan ibadah spiritual, tetapi juga prinsip ekologi dalam ayat-ayat yang mengajarkan tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-A’raf [7]:56) dan pentingnya menjaga keseimbangan (mīzān) dalam kehidupan (QS. Ar-Rahman [55]:7-9).
Tradisi Hindu dan Buddha memiliki akar ekologis yang kuat dalam ajaran dharma (kewajiban moral) dan ahimsa (tanpa kekerasan). Dharma mengajarkan harmoni antara manusia dan alam semesta, sementara ahimsa mendorong penghormatan terhadap seluruh makhluk hidup sebagai bagian dari siklus kehidupan yang saling terhubung. Dalam Bhagavad Gita, Krishna menjelaskan pentingnya hidup yang selaras dengan alam sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Buddhisme, dengan ajaran tentang inter-being dan kesadaran batin, mengajak umatnya untuk menyadari bahwa penderitaan makhluk hidup lain adalah juga penderitaan kita.
Sementara itu, dalam kearifan lokal Nusantara, seperti filosofi Tri Hita Karana di Bali, dikenal konsep keharmonisan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesama (pawongan), dan manusia dengan alam (palemahan). Filosofi ini menjadikan keberlanjutan hidup sebagai hasil dari keseimbangan spiritual dan ekologis. Ritual-ritual adat yang menghormati hutan, sungai, dan gunung sebagai entitas hidup merupakan ekspresi nyata spiritualitas ekologis lokal yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun.
Setiap tradisi ini (dari Barat hingga Timur, dari agama samawi hingga lokal) menawarkan akar teologis yang kokoh untuk menumbuhkan kesadaran ekologis. Sayangnya, dalam praktik modern, ajaran luhur ini sering terlupakan di tengah arus kapitalisme, individualisme, dan eksploitasi alam tanpa batas.
B. Bumi sebagai “Rumah Bersama”
Di era krisis iklim global, penting untuk menegaskan kembali bahwa bumi bukan milik satu bangsa, agama, atau generasi, melainkan rumah bersama (common home) seluruh makhluk hidup. Konsep ini menjadi titik temu lintas spiritualitas dan budaya.
Dalam Islam, banyak ayat suci yang menegaskan bahwa alam semesta adalah tanda-tanda (āyāt) kekuasaan Allah yang harus direnungkan dan dijaga. QS. Al-An’am [6]:141 menegaskan agar manusia tidak melampaui batas dalam memanen hasil bumi: “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”
Hadis Nabi Muhammad ﷺ pun menegaskan pentingnya lingkungan. Dalam satu riwayat disebutkan: “Jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada benih pohon kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya.” (HR. Ahmad). Pesan ini menekankan urgensi berbuat kebaikan ekologis bahkan dalam keadaan genting.
Spiritualitas Timur, seperti dalam Buddhisme dan Taoisme, menekankan interconnectedness atau keterhubungan antara semua makhluk. Dalam ajaran Buddha, semua makhluk terikat oleh hukum sebab-akibat (karma) dan hidup dalam saling ketergantungan. Alam bukan objek pasif, melainkan entitas yang setara dan layak dihormati. Konsep “inter-being” yang diperkenalkan oleh Thich Nhat Hanh, biksu Vietnam yang juga aktivis lingkungan, mengajarkan bahwa “kita tidak bisa menyendok air tanpa menggoyangkan seluruh lautan.” Dalam pandangan ini, kerusakan pada satu bagian alam (seperti deforestasi atau pencemaran sungai) akan berdampak pada keseluruhan sistem kehidupan. Maka menjaga bumi berarti menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, dan menjaga hubungan dengan Tuhan.
Dengan menyadari bumi sebagai rumah bersama, manusia diundang untuk menumbuhkan empati ekologis. Bumi bukan sekadar sumber daya yang bisa diambil sesuka hati, melainkan ruang suci tempat berlangsungnya kehidupan yang harus dijaga dengan cinta, hormat, dan rasa syukur. Spiritualitas yang mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun gerakan ekologis yang berkelanjutan dan menyentuh hati.
3. Krisis Bumi dan Tanggung Jawab Manusia
A. “Ada Apa dengan Bumi?”
Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan panggilan untuk menyadari kondisi nyata planet kita. Laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) menyatakan bahwa suhu global telah meningkat 1,2°C dibandingkan era pra-industri, dan tren ini akan terus berlanjut jika tidak ada perubahan drastis. Perubahan iklim mempercepat mencairnya es di kutub, menaikkan permukaan laut, dan memperburuk bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Selain itu, hilangnya keanekaragaman hayati telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.
Menurut laporan WWF Living Planet Report 2022, populasi spesies vertebrata global telah menurun rata-rata 69% sejak 1970. Hutan tropis (paru-paru bumi) mengalami deforestasi masif demi kepentingan industri dan pertanian. Laut tercemar mikroplastik dan limbah industri, menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang mengancam kehidupan jutaan spesies.
Apa penyebab dari semua ini? Banyak analisis menunjukkan bahwa akar dari krisis ekologi modern bersumber dari paradigma antroposentrisme, yakni pandangan bahwa manusia adalah pusat dari segala ciptaan dan berhak memanfaatkan alam semaunya. Paradigma ini mengaburkan kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem, bukan penguasa absolutnya. Selain itu, konsumerisme modern mendorong manusia untuk hidup berlebihan: membeli lebih dari yang dibutuhkan, mengejar kenyamanan tanpa memikirkan jejak ekologis. “Semakin banyak, semakin baik” telah menjadi nilai sosial yang merusak. Hal ini diperparah oleh sistem ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi berlebihan, di mana alam dijadikan komoditas tanpa mempertimbangkan keberlanjutan.
Dalam konteks ini, manusia telah gagal menunaikan perannya sebagai penjaga bumi. Kita hidup dalam ilusi bahwa teknologi dapat menyelamatkan segalanya, padahal akar krisis ini bukan hanya soal alat, melainkan nilai-nilai dan orientasi hidup yang keliru. Maka, pertanyaan “Ada apa dengan bumi?” sesungguhnya adalah cermin: “Ada apa dengan manusia?”
B. Dosa Ekologis
Krisis ekologis tidak hanya dapat dibaca sebagai bencana lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk dosa kolektif umat manusia. Dalam kerangka teologi Islam, dosa tidak hanya terbatas pada pelanggaran moral individu, tetapi juga mencakup perusakan tatanan ilahi yang telah diciptakan Tuhan dengan sempurna. QS. Ar-Rum [30]:41 menyatakan: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Ayat ini dengan jelas menempatkan manusia sebagai agen utama kerusakan dan menyerukan pertobatan ekologis.
Dalam pandangan Islam, merusak alam adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Tuhan. Bumi diciptakan dalam keseimbangan (mīzān), dan manusia diperintahkan untuk menjaganya, bukan merusaknya. Ketika ekosistem dihancurkan demi keuntungan jangka pendek, kita tidak hanya berbuat zalim terhadap makhluk lain, tetapi juga terhadap generasi mendatang yang akan mewarisi kerusakan tersebut.
Sayangnya, dalam praktik keagamaan sehari-hari, masih banyak umat beragama yang memisahkan spiritualitas dari tindakan ekologis. Pandangan bahwa bumi hanyalah “sarana” atau “alat” menuju akhirat menjadi alasan pembenaran untuk mengabaikan tanggung jawab lingkungan. Padahal, dalam tafsir yang lebih luas, bumi bukan sekadar wadah sementara, melainkan tanda kebesaran Tuhan yang harus dihormati. Dalam Islam, konsep tauhid (pengesaan Tuhan) mengarahkan manusia untuk melihat keterhubungan antara segala ciptaan, termasuk alam semesta, sebagai bagian dari manifestasi kehendak Ilahi.
Pemikir ekoteologi Islam seperti Seyyed Hossein Nasr telah lama mengingatkan bahwa hilangnya kesadaran sakral terhadap alam adalah akar dari krisis ekologis modern. Ia menekankan bahwa dalam peradaban Islam klasik, alam dilihat sebagai ayat-ayat kauniyah (tanda-tanda kosmis), bukan sekadar objek eksploitasi. Ketika alam tidak lagi dianggap suci, maka kekerasan ekologis menjadi hal yang lumrah.
Karenanya, perlu ada perubahan paradigma teologis: dari agama yang hanya menekankan ritual, menuju agama yang juga menghidupkan tanggung jawab ekologis. Dosa ekologis harus menjadi bagian dari kesadaran etis dan spiritual umat beriman. Bertindak merusak bumi bukan hanya tindakan keliru secara sosial dan ilmiah, tetapi juga pelanggaran spiritual terhadap kehendak Ilahi.
4. Dari Spiritualitas ke Aksi Nyata
A. Model Praktis Ekoteologi
Kesadaran spiritual tanpa tindakan nyata hanya akan menjadi narasi hampa. Dalam konteks krisis ekologi saat ini, ajaran agama harus melampaui batas mimbar dan masuk ke ranah aksi. Di Indonesia, berbagai komunitas Muslim mulai menunjukkan praktik ekoteologi yang relevan dan membumi.
Salah satu contoh nyata adalah Pesantren Ekologis Ath-Thaariq di Garut, Jawa Barat. Didirikan oleh Kiai Asep Maoshul Affandy, pesantren ini memadukan pendidikan agama dengan pelatihan pertanian organik, konservasi air, dan pelestarian hutan. Di sini, santri belajar mengaji sekaligus merawat alam sebagai bentuk ibadah. Prinsip khalifah fil ardh (wakil Tuhan di bumi) diterjemahkan dalam tindakan konkret seperti penanaman pohon, pengolahan sampah, dan pemanfaatan energi terbarukan.
Gerakan lain datang dari Komunitas Hijrah Iklim, yang mengajak anak muda Muslim untuk menyuarakan perubahan gaya hidup ramah lingkungan. Mereka mengadakan kampanye “Ramadhan Hijau” dengan mengurangi sampah plastik saat berbuka puasa dan mendorong penggunaan transportasi publik. Aktivisme ini tidak hanya berbasis kesadaran sosial, tetapi juga nilai-nilai Islam seperti zuhud (hidup sederhana) dan amanah terhadap bumi.
Tokoh seperti KH. M. Cholil Nafis dan Hayu Prabowo (Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam – MUI) juga telah menggaungkan pentingnya fatwa ekologis, termasuk Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Fatwa ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap alam bukan sekadar urusan ilmiah atau kebijakan pemerintah, tetapi bagian dari komitmen keagamaan.
Model-model ini membuktikan bahwa ekoteologi bukan sekadar konsep, tetapi dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata melalui kolaborasi lintas sektor: ulama, pesantren, pemuda, dan komunitas lokal.
B. Langkah Konkret Individu dan Komunitas
Untuk menjawab tantangan ekologi global, tidak cukup hanya mengandalkan gerakan kolektif berskala besar. Perubahan besar justru dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten oleh individu dan komunitas.
Langkah pertama adalah hidup sederhana dan mengurangi jejak karbon. Dalam Islam, hidup sederhana adalah nilai luhur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Gaya hidup zuhud, yang menghindari keserakahan, sangat relevan dalam era konsumerisme ini. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, membawa wadah minum sendiri, atau memilih makanan lokal dan musiman adalah bentuk ibadah ekologis yang nyata.
Kedua, advokasi kebijakan berkelanjutan menjadi penting. Umat beragama perlu dilibatkan dalam dialog publik tentang kebijakan lingkungan. Misalnya, mendukung regulasi tentang energi bersih, perlindungan kawasan hutan adat, atau tata kelola limbah yang adil. Agama memiliki kekuatan moral untuk memengaruhi kebijakan, dan suara kolektif dari komunitas spiritual dapat menjadi tekanan positif bagi para pengambil keputusan.
Ketiga, pendidikan ekologi berbasis nilai-nilai spiritual perlu diprioritaskan. Masjid, pesantren, dan majelis taklim dapat menjadi pusat penyadaran lingkungan. Khutbah Jumat, pengajian, bahkan kurikulum madrasah bisa mengintegrasikan ajaran tentang pentingnya menjaga ciptaan Tuhan. Dengan cara ini, ekoteologi tidak hanya hidup dalam teori, tetapi juga tumbuh dalam kesadaran generasi masa depan.
Mengubah relasi manusia dengan bumi membutuhkan waktu, kesabaran, dan keteladanan. Namun, setiap langkah kecil menuju kesadaran ekologis adalah bagian dari ibadah, bagian dari cinta kita kepada Sang Pencipta dan ciptaan-Nya.
5. Penutup
Bumi bukanlah sekadar sumber daya untuk dimanfaatkan, melainkan amanah Tuhan yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab. Dalam perspektif Islam, manusia diberi kehormatan sebagai khalifah – pemelihara kehidupan, bukan perusaknya. Maka, merawat bumi sejatinya adalah bagian dari ibadah; sebuah panggilan suci untuk hidup selaras dengan ciptaan-Nya.
Krisis ekologis hari ini menuntut kolaborasi lintas iman dan keilmuan. Para pemimpin agama, ilmuwan, dan aktivis lingkungan perlu berjalan bersama, membangun kesadaran spiritual sekaligus solusi praktis. Jalan menuju pemulihan bumi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan hati dan nilai.
Kini, saatnya kita bertanya pada diri sendiri:
Bagaimana spiritualitas saya menginspirasi aksi untuk bumi?
Sebagaimana dikatakan oleh Seyyed Hossein Nasr, pemikir ekoteologi Islam:
“Selama manusia memandang alam sebagai benda mati, maka ia akan terus merusaknya. Tetapi jika ia melihatnya sebagai ciptaan Tuhan yang hidup, maka ia akan menjaganya dengan cinta dan hormat.”
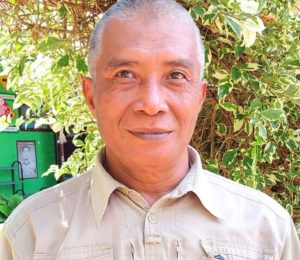
Lukman Hakim : Kepala Biro Kab. Jember